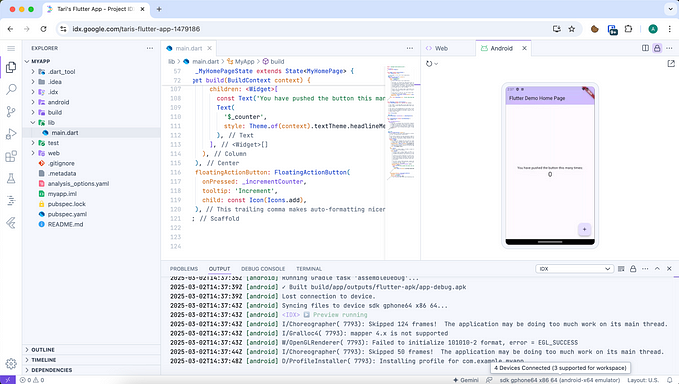LAMPU KUNING KEBEBASAN BERPENDAPAT

“If the freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.”
― George Washington
Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur krusial di dalam dinamika kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Dengan semakin melekatnya platform digital dalam kehidupan masyarakat, seharusnya kebebasan berpendapat pun semakin tidak terhambat. Akan tetapi keresahan masyarakat dan bukti data tidak sepakat.
Survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia semakin takut untuk menyatakan pendapat. Data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pun menunjukkan hal serupa yaitu menurunnya angka kebebasan berpendapat. Selain itu, pada Indeks Kebebasan Pers Dunia 2020 oleh Reporter Without Borders Indonesia masih menempati urutan ke-119 dari total 180 negara.
Namun apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia saat ini sehingga angka-angka dapat berkata demikian? Melalui artikel ini, Tim Penelitian dan Pengembangan Korps Mahasiswa Komunikasi Universitas Gadjah Mada telah menyoal empat buah perkara kebebasan berpendapat di dunia digital yang meliputi UU ITE, buzzer, polisi virtual, dan sudut pandang korban represi kebebasan berpendapat.
Dua Sisi Mata Uang UU ITE
Ketika membahas kebebasan berpendapat di ruang digital di Indonesia, topik UU ITE tentunya menjadi pusat perhatian, karena tidak sedikit masyarakat pengguna media sosial yang menganggap bahwa UU ITE membatasi kebebasan berpendapat. Untuk mengetahui kebenaran dari klaim tersebut, kita perlu meninjau ulang UU ITE dimulai dari sejarah dan latar belakangnya hingga pasal-pasal “karet” UU ITE, wacana revisi UU ITE oleh Jokowi, dan tidak masuknya revisi UU ITE tersebut ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
UU ITE atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai dirancang di bawah pemerintahan Presiden Megawati sebagai gabungan dari RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi yang disusun oleh Universitas Padjajaran dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Universitas Indonesia. UU ITE kemudian disahkan di tahun 2008 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tujuan awal dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna platform digital. Keseluruhan undang-undang tersebut mengatur tentang e-commerce, tindak pidana teknologi informasi yang meliputi konten ilegal, SARA, kebencian, hoaks, penipuan, pornografi, judi, hingga pencemaran nama baik, dan perkara lain meliputi akses ilegal, seperti hacking, penyadapan, serta gangguan atau perusakan sistem secara ilegal.
Pertanyaannya adalah apakah tujuan awal pembentukan UU ITE terpenuhi? Atau apakah klaim bahwa UU ITE membatasi kebebasan berpendapat memang benar terjadi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa pasal-pasal yang dianggap “karet” atau bermasalah karena bersifat multitafsir mencakup pasal 27 yang mengatur perkara pencemaran nama baik, pasal 28 mengatur perkara ujaran kebencian, dan pasal 29 yang berguna untuk menjerat pelaku pengancaman melalui media sosial. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej pada tahun 2021 juga menilai bahwa pasal 27, 28, dan 29 UU ITE tidak jelas.
Terkait klaim-klaim pasal karet tersebut, pada tahun 2016 Jokowi telah merevisi UU ITE dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008. Akan tetapi ternyata revisi tersebut tidak mencakup pasal-pasal yang dipermasalahkan tadi. Padahal berdasarkan data dari Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet), sejak tahun 2008 hingga 2018 terdapat sekitar 381 korban UU ITE, dan 90 persen di antaranya dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik yang pasalnya karet itu. Kemudian setelah undang-undang tersebut direvisi hingga tahun 2020, terdapat kasus-kasus dengan pasal 27, 28, dan 29 dengan tingkat penghukuman mencapai 96,8 persen atau 744 perkara dengan 676 perkara di antaranya berupa pemenjaraan.
Meskipun pemerintah sendiri pada tahun 2017 melalui Dirjen Aplikasi Informatika mengklaim bahwa pasal-pasal yang bermasalah di atas tidak membatasi kebebasan berpendapat masyarakat, berdasarkan data dari Amnesty International Indonesia, hanya di dalam tahun 2020 saja terdapat 119 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE. SAFEnet menjelaskan bahwa terdapat pola pemidanaan dari laporan yang mencantumkan UU ITE, yakni balas dendam, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Ika Ningtyas menilai UU ITE menjadi upaya untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik, dengan melihat bahwa sementara sebagian besar korban adalah jurnalis, aktivis, dan warga, sebagian besar pelapor berasal dari kalangan pejabat, aparat dan pemodal.
Terkait semakin viralnya klaim-klaim pembatasan kebebasan berpendapat oleh UU ITE, pada bulan Februari 2021, Presiden Jokowi berwacana lagi untuk merevisi UU ITE. Mengutip dari Twitter resmi Presiden Jokowi pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jokowi menyatakan, “Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi.” Akan tetapi, ternyata wacana Revisi UU ITE tersebut tidak terdaftar di dalam Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas 2021 dengan alasan pemerintah masih menampung aspirasi publik.
Pemerintah Berkelit, Buzzer Menggigit
Istilah buzzer atau pendengung juga tentunya sudah tidak asing bagi pengguna platform digital Indonesia. Pengertian umum buzzer adalah akun-akun media sosial yang tidak jelas identitasnya sehingga tidak memiliki reputasi yang dipertaruhkan. Buzzer biasanya memiliki agenda atau motif ideologis atau ekonomi tertentu dalam menyebarkan informasi yang tidak jelas pula kebenarannya di media sosial. Buzzer juga ada yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu dan ada pula yang sukarela.
Lalu apa kaitannya buzzer dengan kebebasan berpendapat di dunia digital Indonesia? Selain UU ITE, keberadaan buzzer juga dianggap dapat membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Ika Ningtyas dan juga Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas berpendapat bahwa di situasi saat ini pengguna media sosial yang mengkritisi kinerja atau kebijakan pemerintah dapat dengan mudahnya menerima serangan digital dari buzzer bahkan hingga dilaporkan dengan UU ITE.
Ironisnya, UU ITE yang notabene bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat di ruang digital tersebut malah tidak memiliki undang-undang yang mengatur mengenai buzzer. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa memang tidak ada aturan yang mengatur buzzer, bahkan di dalam UU ITE. Alasannya adalah karena buzzer, influencer, dan endorser dianggap sama di mata pemerintah, bahwa semuanya tidak melanggar undang-undang apapun.
Tragis apabila melihat data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa pada sepanjang 2014 hingga 2019, pemerintah pusat sendiri mengeluarkan dana sebesar Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer individu dan kelompok, dengan tujuan mempengaruhi opini publik mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Tercatat juga oleh ICW bahwa metode oleh pemerintah tersebut semakin meningkat penggunaannya sejak tahun 2017.
Kata Mereka yang Pernah Bersuara
Poin-poin di atas sepertinya juga sudah menggambarkan bagaimana undang-undang ini bekerja dan dapat menjadi sebuah rangkuman kecil bagi pembaca untuk bisa melihat sepak terjang undang-undang ini dalam beberapa tahun terakhir ini.
Masih berbicara mengenai undang-undang ITE, banyak pakar berpendapat bahwa sepertinya revisi UU ITE ini harus menjadi sebuah urgensi tersendiri untuk direvisi oleh para pemangku jabatan. Bagaimana tidak? Pasal-pasal karet yang sudah diperingatkan sudah acapkali memakan korban. Hal tersebut dapat kita lihat dari tujuannya yang melenceng dari titik awal, penyalahgunaan dari beberapa oknum untuk merepresi, dan pembungkaman opini dan juga suara orang yang ingin bersuara.
Dandhy Laksono, mungkin nama itu masih terdengar asing bagi para pembaca kanal info ini. Mantan jurnalis sekaligus pendiri Wachdoc Documentaries ini pernah menjadi salah satu orang yang mencicipi pahitnya UU ITE pada tahun 2019 silam. Dandhy Laksono ditangkap karena diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 A ayat (2) UU №8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 №1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Jika ingin disimplifikasi, Dandhy Laksono ditangkap karena cuitannya di Twitter yang dianggap sebagai provokasi.
Tidak hanya aktivis/jurnalis saja yang seakan-akan diincar oleh UU ITE ini, masyarakat biasa pun sepertinya terkena imbasnya, salah satunya adalah cerita mengenai Saidah Saleh Syamlan. Seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam melakukan sosialisasi. Peristiwa di akhir 2017 pun sangat terkenang dan menjadi suatu pengalaman tersendiri olehnya. Ia ditangkap dan disidik mengenai kasus pencemaran nama baik PT Prisma Putra Textile. Proses hukum pun mau tidak mau harus ia hadapi yang berujung dijatuhkannya vonis hukuman ke Saidah selama 10 bulan dengan denda Rp 5 juta karena akhirnya ia “terbukti” melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) ITE tentang pencemaran nama baik (tentu kasusnya tidak hanya selesai sampai sini dan masih berlanjut sampai sekarang).
Jika dilihat di antara dua kasus tersebut, kita dapat melihat sebuah persamaan yang muncul. Untuk kasus pertama, Dandhy laksono ditangkap karena diduga telah melakukan provokasi, jika dilihat dari sudut pandang polisi/pelapor. Kasus kedua, Saidah juga disidik karena diduga telah mencemarkan nama baik perusahaan, dilihat dari sudut pandang pelapor. Sebuah pola pun sudah mulai terlihat. banyak yg berpendapat bahwa pasal-pasal pemidaan yang ada di UU ITE sangatlah samar dan juga bersifat subjektif. Hal itu juga pernah diutarakan oleh Erasmus Napitupulu, Direktur Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), jika dilansir dari salah satu artikel di Tirto.ID pada tahun 2021.
Penjaga Digital, “Sang” Polisi Virtual
Belum selesai dengan permasalahan UU ITE, para pemangku jabatan sekali lagi menerbitkan sebuah “inovasi” terbaru. Dilansir dari Kompas, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan segera mengaktifkan Virtual Police. Tidak lupa dalam mengemban program ini, Polri juga menggandeng Kominfo untuk melakukan koordinasi pembentukan satuan khusus digital.
Dikutip dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Ahmad Ramadhan, nantinya Virtual Police ini akan berpatroli di dunia maya, seperti media sosial, untuk “menegur” dan juga “mengedukasi” para pengguna jika ada yang berpotensi melanggar UU ITE.
Masih di seputaran UU ITE, Virtual Police digadang-gadang merupakan sebuah tindakan respons dari Polri terkait arahan Presiden Joko Widodo soal pasal-pasal karet yang ada di UU ITE dan merupakan sebuah upaya penindaklanjutan dari surat edaran kapolri mengenai perwujudan Ruang Digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Lantas, bagaimana sepak terjang Virtual Police setelah beberapa bulan setelah pengaktifannya?
Dilihat dari Kompas.com (24/2/2021), Virtual Police sudah berhasil memberikan teguran ke setidaknya tiga akun media sosial. Salah satu akun yang ditegur adalah akun yang bernama @PA_009. Konten media sosial (Twitter) tersebut berpotensi pidana ujaran kebencian. Polri berharap dengan adanya teguran tersebut dapat mengurangi konten-konten hoaks di media sosial. Selain itu, masyarakat juga lebih “hati-hati”.
Dilihat dari sudut pandang lain, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengkritik adanya pengaktifan virtual police di dunia digital guna memantau pergerakan masyarakat. SAFEnet menambahkan bahwa alih-alih memberikan rasa aman dalam bermedia sosial dan juga berinteraksi, adanya Virtual Police justru menciptakan ketakutan baru. Ketakutan tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar karena aksi Virtual Police dinilai terlalu jauh masuk ke ruang privat digital warga, mengancam kebebasan berekspresi, dan menciptakan sebuah kondisi yang orwellian.
Penutup
Banyak permasalahan lainnya yang tidak mungkin dapat dicantumkan di tulisan ini dan tidak perlu dijabarkan secara terperinci satu per satu. Sudah saatnya kita sadar bahwa fakta dan cerita di atas sudah cukup untuk menjadi cerminan kita sebagai manusia dan warga negara bahwa represi kebebasan berekspresi ataupun kebebasan berpendapat itu nyata adanya. Padahal, jika kita lihat lagi, negara kita merupakan negara yang paling lantang berteriak dalam menerapkan pilar-pilar demokrasi.
Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara dan kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dalam dunia demokrasi. Ketiga hal tersebut bersifat terikat satu dengan yang lainnya. Evaluasi dari para pemangku kepentingan sepertinya sudah menjadi sebuah urgensi karena jika tidak, bukan tidak mungkin hak manusia dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat tahun-tahun ke depan akan semakin jauh dari harapan.
Penutup kanal info edisi ini diharapkan bukan menjadi sebuah titik akhir dari seorang pembaca, melainkan menjadi sebuah titik awal ataupun pemantik untuk para pembaca mengenai permasalahan di atas. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tentunya mengawal dan juga mendorong adanya evaluasi-evaluasi kebijakan yang merugikan tersebut dan tentunya untuk tidak takut bersuara dan berpendapat karena sekecil apapun teriakan tersebut, adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umumlah yang memanusiakan kita sebagai manusia.
Ditulis dan dikelola oleh:
- Alfredo Dwiputra Ardiansyah
- Florencia Azella Setiajid